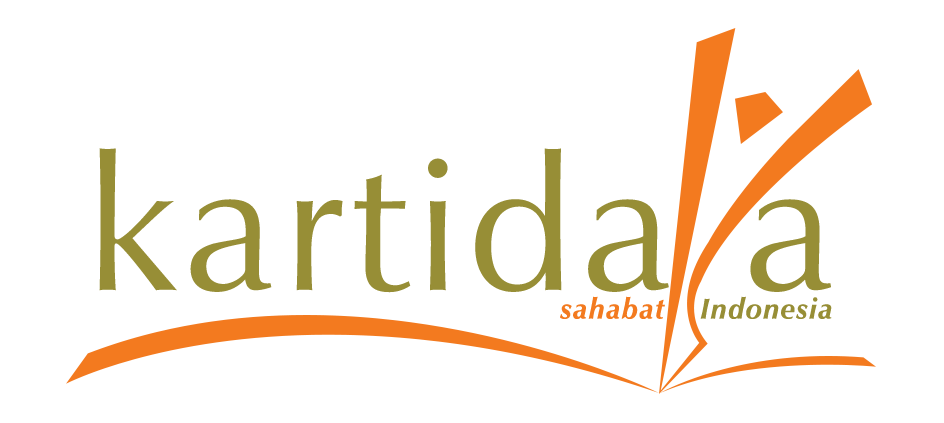Integritas seorang fasilitator atau pendamping penerjemahan tidak hanya tampak saat mereka duduk bersama tim untuk menerjemahkan Firman Tuhan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari—saat mereka dihadapkan pada kebutuhan orang lain, godaan untuk menutup mata terhadap kesusahan, atau saat berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Ketika seorang pendamping dianggap mewakili lembaga, bahkan Firman Tuhan itu sendiri, maka sikap mereka bisa memperkuat atau justru melemahkan kesaksian pelayanan.
Sejak awal diutus ke Suku Dou – Papua, Kukuh dan Risma menyadari bahwa pelayanan ini bukan sekadar soal bahasa. Jaringan telepon tidak selalu tersedia, transportasi terbatas, dan akses terhadap layanan kesehatan sangat minim. Dua kali dalam setahun—selama beberapa kali—mereka berupaya membawa tenaga medis dari luar. Namun di antara waktu-waktu itu, merekalah yang harus merangkap peran: pendeta, konselor, tukang masak, bahkan “dokter” darurat bagi siapa pun yang membutuhkan. Di mata masyarakat, mereka bukan lagi sekadar penerjemah atau tamu. Mereka sudah seperti orang tua bagi satu suku—sosok yang dianggap serba bisa.
Namun mereka pun memiliki keterbatasan. Tidak semua hal bisa mereka jawab atau tangani. Tapi Kukuh dan Risma tidak berhenti hanya karena merasa itu “di luar tanggung jawab.” Mereka percaya bahwa memberitakan Yesus tidak bisa dipisahkan dari kehadiran yang penuh kasih—yang peduli, menyentuh, dan sungguh-sungguh hadir bagi sesama.
Pelayanan mereka bukanlah kisah besar yang dramatis. Justru dalam keseharian yang sederhana—menolong, hadir, mendengar, dan setia di tengah keterbatasan—mereka menyampaikan pesan Firman itu sendiri.